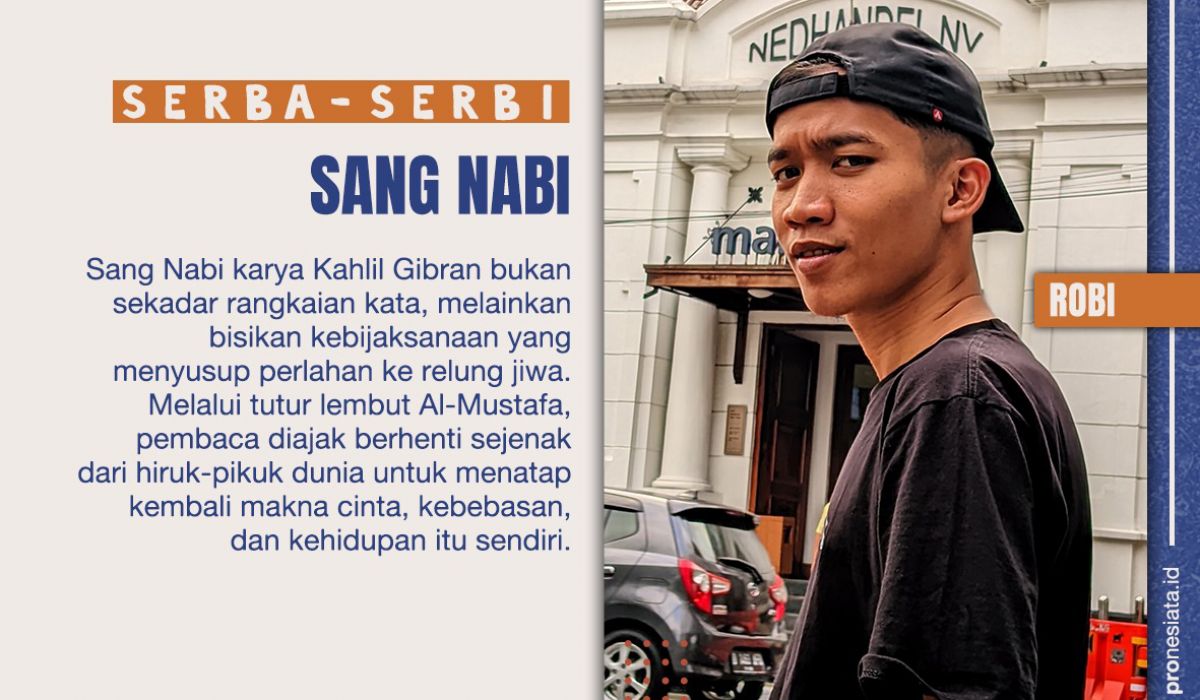Kehidupan Tanpa Arah
Rika duduk di sudut kamar berukuran tiga kali empat meter yang terasa lebih seperti penjara daripada tempat tinggal. Dindingnya polos, tanpa hiasan, dan hanya ada satu jendela kecil yang mengarah ke luar.
Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat cahaya lampu jalan yang temaram, tapi tidak ada apa pun di luar sana yang menarik perhatiannya. Dunia luar terasa seperti sesuatu yang jauh, sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari hidupnya.
Di atas meja kecil di samping tempat tidurnya, ada tumpukan buku-buku kuliah yang berantakan. Sebagian besar belum disentuh. Di dalam hatinya, Rika tahu ia harus belajar, harus mempersiapkan diri untuk ujian minggu depan. Tapi ia tidak bisa. Ia tidak punya energi, tidak punya motivasi. Apa gunanya semua ini? pikirnya. Ia merasa seperti berjalan tanpa arah, mengikuti arus kehidupan tanpa tahu ke mana ia sebenarnya ingin pergi.
Rika adalah mahasiswi berusia dua puluh tahun yang menjalani kehidupannya dengan sunyi. Ia bukan orang yang mudah berbicara, bukan seseorang yang bisa dengan mudah membuka hati kepada orang lain. Ia lebih suka menyimpan semuanya sendiri—rasa sakit, kesedihan, bahkan kebahagiaan kecil yang sesekali muncul. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam pikirannya, dan Rika tidak ingin mereka tahu.
Dalam kesehariannya, Rika adalah seorang introvert yang ekstrem. Ia tidak pernah mencari perhatian, tidak pernah mencoba untuk menonjol. Ia berjalan di lorong kampus dengan kepala menunduk, menghindari tatapan mata siapa pun. Saat dosen bertanya di kelas, ia tidak pernah mengangkat tangan.
Bahkan ketika ia tahu jawabannya, lidahnya terasa kelu, dan jantungnya berdegup kencang hanya dengan memikirkan berbicara di depan semua orang.
Di dunia yang penuh keramaian, Rika merasa seperti bayangan. Ia ada di sana, tapi tidak pernah benar-benar terlihat. Namun, yang paling menyakitkan bagi Rika bukanlah bagaimana dunia memperlakukannya, melainkan bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Ia sering merasa bahwa dirinya adalah musuh terburuknya.
Setiap malam, saat ia berbaring di tempat tidur, pikirannya dipenuhi dengan suara-suara yang terus menghakimi. “Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu tidak bisa jadi seperti orang lain? Kenapa kamu tidak pernah cukup baik?”
Rika selalu menangis diam-diam di kamar, memastikan tidak ada yang mendengar. Ia tidak ingin ada yang tahu bahwa ia rapuh, bahwa ia merasa seperti pecundang. Bahkan kepada lima orang teman terdekatnya—satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya—ia tidak pernah benar-benar jujur.
Mereka mencoba mendekatinya, mencoba membuatnya terbuka, tapi Rika selalu memasang tembok. Ia takut. Takut dihakimi, takut ditinggalkan, takut bahwa jika mereka tahu siapa dirinya sebenarnya, mereka tidak akan mau berteman dengannya lagi.
Malam itu, seperti banyak malam lainnya, Rika menatap langit-langit kamarnya dengan mata yang basah. Ia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Ia tidak tahu kenapa ia selalu merasa kosong, meskipun ia memiliki teman, memiliki keluarga, memiliki semua hal yang seharusnya membuatnya merasa bahagia.
Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi rasa hampa itu tetap ada, seperti lubang gelap yang tidak pernah bisa ia isi. Rika memejamkan mata, berharap bahwa tidur akan membebaskannya dari perasaan ini, meskipun hanya untuk sementara.
Tapi bahkan dalam mimpinya, ia sering merasa tersesat. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari kegelapan ini.
***
Pagi itu, Rika memaksa dirinya untuk bangun dari tempat tidur. Alarm di ponselnya sudah berbunyi tiga kali, tetapi ia hanya menekan tombol hening tanpa niat untuk benar-benar bangun. Akhirnya, setelah menatap langit-langit selama beberapa menit, ia menyeret tubuhnya ke kamar mandi. Air dingin yang mengalir tidak cukup untuk mengusir rasa lelah yang mendera, bukan lelah fisik, tapi lelah yang datang dari dalam.
Hari ini seperti hari-hari lainnya—kuliah, duduk di pojok kelas, mendengar dosen berbicara, lalu pulang tanpa berbicara dengan siapa pun. Itu adalah rutinitas yang sudah ia jalani selama hampir dua tahun. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda.
Rika tiba di kampus beberapa menit sebelum kelas dimulai. Ia berjalan cepat melewati lorong, menghindari tatapan teman-temannya. Ia tidak ingin terlihat. Ia tidak ingin ada yang menyapanya. Bukan karena ia membenci mereka, tetapi karena ia tidak tahu bagaimana harus merespons.
Setiap kali seseorang mencoba berbicara dengannya, pikirannya langsung dipenuhi dengan kekhawatiran: “Apa yang harus aku katakan? Bagaimana kalau aku mengatakan sesuatu yang salah? Bagaimana kalau mereka menertawakanku?”
Ia masuk ke dalam kelas dan duduk di sudut belakang, tempat favoritnya. Dari sana, ia bisa mengamati semua orang tanpa harus terlibat. Teman-teman sekelasnya berbicara dengan penuh semangat, membahas tugas kuliah, acara kampus, atau hal-hal sepele lainnya. Rika hanya mendengarkan dari kejauhan, mencoba memahami bagaimana mereka bisa begitu santai dan terbuka.
Ketika dosen masuk, suasana kelas perlahan menjadi tenang. Rika membuka buku catatannya, meskipun ia tahu tidak banyak yang akan ia tulis. Ia selalu membawa buku itu sebagai bentuk formalitas, sesuatu yang membuatnya terlihat seperti mahasiswa pada umumnya. Tapi pikirannya sering melayang, jauh dari materi yang diajarkan.
Di tengah kuliah, dosen mengajukan pertanyaan kepada kelas. Beberapa mahasiswa mengangkat tangan dengan antusias, berebut untuk memberikan jawaban. Rika tahu jawabannya, tapi seperti biasa, ia tidak berani berbicara. Ia hanya menunduk, berharap tidak ada yang memperhatikannya.
“Kamu tahu jawabannya, Rika?” Suara dosen itu tiba-tiba memanggil namanya, membuat jantungnya berdegup kencang.
Rika mendongak dengan wajah panik. Semua mata di kelas tertuju padanya. Ia mencoba membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya terasa kering, dan pikirannya kosong. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dosen itu akhirnya beralih ke mahasiswa lain.
Rika menunduk, merasa malu dan marah pada dirinya sendiri. “Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku tidak bisa melakukan hal sederhana seperti menjawab pertanyaan?” Pikiran itu terus menghantui sepanjang sisa kuliah.
Saat kelas berakhir, Rika dengan cepat merapikan barang-barangnya dan keluar sebelum ada yang sempat berbicara dengannya. Ia berjalan menuju perpustakaan, tempat yang selalu menjadi pelariannya. Perpustakaan adalah tempat di mana ia bisa tenggelam dalam keheningan, jauh dari tatapan dan suara orang-orang.
Di salah satu sudut perpustakaan, Rika duduk sendirian dengan buku yang terbuka di depannya. Tapi matanya tidak benar-benar membaca. Pikirannya terlalu sibuk dengan monolog batin yang tidak pernah berhenti.
“Apa gunanya semua ini?” bisiknya pada diri sendiri. “Aku hanya menjalani hidup tanpa arah. Aku tidak punya tujuan, tidak punya mimpi. Aku hanya... ada-”
Rika sering bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia cari dalam hidup ini. Ia tidak memiliki jawaban. Ia hanya mengikuti arus, melakukan apa yang diharapkan darinya, tanpa benar-benar tahu ke mana ia ingin pergi.
Kadang-kadang, ia melihat teman-temannya berbicara tentang impian mereka—menjadi dokter, insinyur, atau pengusaha sukses. Tapi bagi Rika, semua itu terasa seperti sesuatu yang jauh di luar jangkauannya.
Ia bahkan tidak yakin apakah ia bisa lulus kuliah. Ketika sore tiba, Rika pulang ke kosan-nya. Ia melewati teman-temannya yang sedang duduk di ruang bersama, tertawa dan bercanda. Salah satu dari mereka, Hana, melambaikan tangan ke arahnya.
“Hai, Rika! Mau gabung?” tanya Hana dengan senyuman ramah.
Rika tersenyum kecil, tapi ia menggeleng. “Tidak, terima kasih. Aku mau istirahat,” jawabnya pelan. Hana mengangguk, meskipun jelas terlihat bahwa ia kecewa. Rika tahu bahwa teman-temannya hanya ingin mengajaknya bergabung, mencoba membuatnya merasa diterima. Tapi ia tidak bisa. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap di tengah keramaian.
Malam itu, seperti biasa, Rika duduk di sudut kamarnya. Ia menatap buku catatannya, mencoba menulis sesuatu, tapi tidak ada yang keluar. Ia merasa kosong, seperti perahu kecil yang terombang-ambing di tengah lautan tanpa tujuan. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi ia tidak membuat suara. Tangisannya selalu sunyi, seperti dirinya.
***
Di malam yang sunyi itu, Rika memandangi dirinya sendiri di cermin kecil di sudut kamarnya. Wajah yang ia lihat di sana terasa asing. Matanya bengkak karena terlalu sering menangis, kulitnya terlihat pucat, dan ekspresinya datar—seperti seseorang yang hidup hanya karena harus, bukan karena ingin. Ia bertanya-tanya, “Sejak kapan aku menjadi seperti ini?”
Pikirannya melayang ke masa lalu, ke hari-hari yang seharusnya penuh dengan tawa, tetapi malah dipenuhi dengan luka yang tidak bisa ia lupakan. Rika tidak pernah menjadi anak yang populer. Sejak kecil, ia selalu menjadi “anak yang diam,” yang jarang berbicara dan lebih suka duduk sendirian di sudut kelas.
Ia bukan karena tidak ingin berteman, tapi karena ia tidak tahu bagaimana caranya. Kata-kata selalu terasa sulit baginya, seperti ada tembok besar yang memisahkannya dari orang-orang di sekitarnya.
Di sekolah dasar, Rika sering menjadi sasaran ejekan teman-temannya. Mereka mengejek suaranya yang pelan, caranya berjalan, bahkan cara ia berpakaian. Hal-hal kecil yang seharusnya tidak penting menjadi bahan olokan. Pernah suatu kali, seorang teman sekelasnya dengan sengaja menyembunyikan buku catatan Rika, membuatnya dihukum oleh guru karena tidak menyelesaikan tugas.
Saat itu, Rika hanya bisa menunduk, menahan air mata, karena ia tahu bahwa jika ia menangis, mereka hanya akan menertawakannya lebih keras.
Pengalaman itu terus berlanjut hingga ia remaja. Di sekolah menengah, ia mencoba untuk berubah. Ia mencoba berbicara lebih banyak, mencoba tersenyum lebih sering, mencoba menjadi seseorang yang “normal.” Tapi usahanya tidak pernah dihargai. Beberapa teman menganggapnya aneh, sementara yang lain hanya mengabaikannya.
Ada satu insiden yang selalu teringat dalam benaknya, yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Saat itu, ia duduk di kelas 2 SMA. Ia berusaha keras untuk bergabung dengan kelompok teman-temannya yang sedang membahas sesuatu. Ia mengumpulkan keberanian untuk berbicara, tetapi sebelum ia selesai berbicara, salah satu dari mereka menyela dengan tawa kecil. “Kenapa suaramu kecil sekali? Kalau mau bicara, bicara yang jelas dong,” kata mereka sambil tertawa.
Rika langsung terdiam. Wajahnya memerah, dan ia merasa seperti ingin menghilang di tempat itu juga. Setelah kejadian itu, ia berhenti mencoba. Ia berhenti berbicara, berhenti berusaha untuk diterima. Ia membangun tembok di sekeliling dirinya, tembok yang semakin hari semakin tebal.
Di balik tembok itu, Rika merasa aman. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Tapi di saat yang sama, ia juga merasa sendirian.
***
Kini, di usia 20 tahun, Rika masih membawa luka-luka itu bersamanya. Ia tahu bahwa ia seharusnya melepaskan masa lalu, tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setiap kali ia mencoba untuk membuka diri, bayangan masa lalu kembali menghantuinya, mengingatkannya pada rasa sakit yang pernah ia alami.
Namun, ada lima orang teman yang tetap bertahan di sisinya, meskipun Rika tidak pernah benar-benar menunjukkan perasaannya kepada mereka. Hana adalah salah satunya. Ia adalah sosok yang ceria dan selalu berusaha mengajak Rika untuk bergabung dengan teman-teman lainnya.
Meski Rika sering menolak, Hana tidak pernah menyerah. Ia selalu mengatakan, “Aku tahu kamu butuh waktu, Rika. Aku di sini kalau kamu butuh.”
Kemudian ada Ali, teman sekelas Rika yang pendiam, tetapi selalu memperhatikan. Ia tidak banyak bicara, tetapi sering membantu Rika tanpa diminta, seperti meminjamkan catatan atau membawakan buku yang tertinggal. Tiga orang lainnya—Rain, Lily, dan Fauzi—adalah teman-teman dari kelompok belajar kecil yang sering Rika ikuti.
Mereka tahu bahwa Rika tidak banyak berbicara, tetapi mereka tetap menerima kehadirannya tanpa tekanan. Meski mereka peduli, Rika merasa bahwa ia tidak pantas menerima perhatian mereka. Ia merasa bahwa ia hanya menjadi beban, seseorang yang tidak pernah benar-benar memberikan apa-apa dalam hubungan itu.
Malam itu, Rika memandangi ponselnya. Ada pesan dari Hana: “Rika, besok kita pergi bareng, ya? Aku jemput kamu jam 9. Jangan bilang tidak, oke?”
Rika tersenyum kecil, meskipun ia tahu bahwa ia mungkin akan menolak lagi. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan bahwa ia merasa lelah, bukan secara fisik, tetapi secara emosional. Ia menutup ponselnya dan memejamkan mata. Air mata kembali mengalir, seperti malam-malam sebelumnya. Luka-luka itu masih ada, meskipun ia berusaha menyembunyikannya.
Di dalam hatinya, Rika tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana cara keluar dari kegelapan ini.
***
Pagi itu, seperti biasa, Rika berangkat ke kampus dengan langkah berat. Ia mengenakan hoodie abu-abu kesukaannya, sesuatu yang membuatnya merasa sedikit lebih terlindungi dari dunia luar. Di dalam keramaian kampus, ia merasa seperti hantu yang melayang tanpa arah, tidak terlihat, tidak terdengar. Itu adalah perasaan yang sudah terlalu akrab baginya.
Namun, hari ini terasa sedikit berbeda. Sejak ia tiba di kelas, suasana hatinya sudah tidak karuan. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Ia tahu apa itu—presentasi kelompok yang akan berlangsung hari ini.
Rika benci berbicara di depan umum. Ia benci menjadi pusat perhatian, meskipun hanya untuk beberapa menit. Tapi kali ini, ia tidak punya pilihan. Teman-teman kelompoknya telah memutuskan bahwa ia yang akan menjadi pembicara, dan ia tidak memiliki keberanian untuk menolak.
Hana, yang duduk di sebelahnya, menatapnya dengan senyum lembut. “Kamu pasti bisa, Rika. Jangan terlalu khawatir,” katanya.
Rika hanya mengangguk pelan. Ia ingin percaya pada kata-kata Hana, tetapi rasa takutnya terlalu besar. Di dalam pikirannya, ia sudah membayangkan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi: suaranya yang gemetar, orang-orang yang menertawakannya, atau yang lebih buruk, keheningan canggung yang memalukan.
Ketika giliran kelompoknya tiba, Rika berjalan ke depan kelas dengan tangan yang gemetar. Ia memegang kertas kecil berisi poin-poin presentasi, tetapi huruf-huruf di atasnya terlihat kabur. Ia merasa seperti sedang berdiri di tengah panggung besar dengan lampu sorot yang menyilaukan, padahal hanya ada dua puluh orang di kelas itu.
“Selamat pagi,” katanya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar.
Beberapa detik berlalu tanpa suara. Rika merasa seperti waktu berhenti, dan ia ingin sekali melarikan diri. Tapi kemudian, ia mendengar suara Hana dari belakang. “Kamu bisa, Rika,” bisik Hana dengan penuh keyakinan. Rika menarik napas dalam-dalam dan mencoba lagi. “Kami akan membahas tentang...” Ia melanjutkan dengan suara yang sedikit lebih kuat, meskipun masih bergetar.
Kata-kata itu keluar dengan sulit, seperti menarik sesuatu dari dalam lubang yang dalam. Tapi ia terus berbicara, meskipun pikirannya dipenuhi dengan ketakutan.
Ia tidak tahu bagaimana ia bisa melewati detik demi detik yang terasa seperti selamanya, tetapi akhirnya ia sampai di akhir presentasinya. Ketika ia kembali ke tempat duduknya, jantungnya masih berdebar kencang. Ia merasa lega, tetapi juga lelah.
“Kamu hebat,” kata Hana sambil tersenyum. “Aku tahu kamu bisa melakukannya.”
Rika hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Di dalam hatinya, ia merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri, meskipun ia tidak akan pernah mengakuinya. Tapi perasaan itu hanya bertahan sebentar, karena suara kecil di dalam kepalanya kembali berbicara.
"Itu tidak sebaik yang kamu pikirkan. Orang-orang mungkin hanya bersikap sopan. Mereka sebenarnya menertawakanmu dalam hati." Monolog batin itu terus menghantuinya sepanjang hari, membuatnya kembali meragukan dirinya sendiri.
***
Malam harinya, Rika duduk di atas tempat tidurnya dengan buku catatan di pangkuannya. Ia mencoba menulis sesuatu, tetapi pikirannya terlalu kacau. Air mata mulai mengalir di pipinya, seperti malam-malam sebelumnya. “Kenapa aku seperti ini?” bisiknya pada dirinya sendiri. “Kenapa aku tidak bisa menjadi seperti orang lain? Kenapa aku selalu merasa tidak cukup?” Ia menutup matanya dan membiarkan air mata itu mengalir.
Namun, di tengah tangisannya, sebuah pikiran muncul di benaknya—sebuah pertanyaan yang telah lama ia hindari. "Apakah aku ingin terus hidup seperti ini?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Ia tidak tahu jawabannya. Ia tahu bahwa ia tidak bahagia, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana caranya untuk berubah.
Di tengah keheningan itu, Rika merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa ia tidak bisa terus mengabaikan perasaannya sendiri. Ia tidak bisa terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, Rika merasa bahwa ia perlu menghadapi dirinya sendiri. Ia perlu menerima bahwa ia terluka, bahwa ia rapuh, dan bahwa tidak apa-apa untuk merasa seperti itu.
***
Hari itu, Rika bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada yang benar-benar berubah dalam hidupnya, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergeser. Mungkin itu adalah dorongan kecil dari dirinya sendiri, atau mungkin itu adalah suara Hana yang terus menguatkan bahwa ia bisa.
Apa pun itu, Rika merasa bahwa ia perlu mencoba. Ia tahu bahwa ia tidak bisa tiba-tiba menjadi orang yang terbuka atau percaya diri, tetapi ia ingin mengambil langkah kecil—langkah yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi berarti besar untuk dirinya sendiri.
Di sela-sela jam kuliah, Rika duduk di taman kampus, mencoba membaca buku. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat suasana terasa tenang, tetapi pikiran Rika tidak bisa berhenti memikirkan apa yang akan ia lakukan. Dari kejauhan, ia melihat Hana berjalan mendekatinya dengan senyum cerah seperti biasa. “Hai, Rika. Lagi sendiri?” tanya Hana sambil duduk di sampingnya tanpa menunggu jawaban.
Rika mengangguk pelan. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin memulai percakapan, tetapi kata-kata itu terasa tersangkut di tenggorokannya. “Kalau kamu mau, nanti kita bisa makan siang bareng sama yang lain,” ajak Hana sambil membuka bekalnya. “Tapi kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa kok. Aku Cuma mau kamu tahu, kamu selalu punya tempat.”
Hana tidak pernah memaksakan apa pun pada Rika, dan itu membuat Rika merasa sedikit lebih nyaman. Ia menatap Hana beberapa detik, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. “Mungkin lain kali,” gumam Rika akhirnya.
Hana tersenyum. “Oke. Nggak masalah kok.”
Percakapan itu singkat, nyaris tidak berarti untuk orang lain, tetapi bagi Rika, itu adalah langkah kecil yang besar. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya menolak dengan anggukan atau senyuman, tetapi dengan kata-kata.
Beberapa hari kemudian, Rika mendengar kabar tentang lomba menulis esai yang diadakan oleh kampus. Ia melihat poster itu terpampang di mading, tetapi ia segera mengabaikannya. “Buat apa aku ikut? Aku tidak akan menang,” pikirnya.
Namun, selama beberapa hari berikutnya, poster itu terus terbayang di pikirannya. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ada bagian kecil dari dirinya yang ingin mencoba. Menulis adalah sesuatu yang selalu ia sukai, meskipun ia jarang membagikannya kepada orang lain.
Malam itu, Rika duduk di depan laptopnya dengan layar kosong di depannya. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Jari-jarinya gemetar di atas keyboard, dan pikirannya dipenuhi dengan keraguan. “Bagaimana kalau tulisanku jelek? Bagaimana kalau mereka menertawakannya?”
Tetapi kemudian, ia teringat pada percakapan kecil dengan Hana di taman. Ia teringat bagaimana rasanya membuat langkah kecil, meskipun itu sulit. Dan dengan napas dalam, Rika mulai mengetik. Kata-kata itu keluar perlahan, tetapi setiap huruf terasa seperti kemenangan kecil.
Esai itu selesai beberapa jam kemudian. Judulnya sederhana: “Sunyi yang Tak Terlihat.” Dalam esai itu, Rika menuangkan semua perasaan dan pikirannya—tentang bagaimana rasanya menjadi seseorang yang terus merasa tidak cukup, tentang ketakutan yang selalu menghantui, dan tentang keinginan kecil untuk berubah.
Esai itu mungkin tidak sempurna, tetapi itu adalah cerminan dirinya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa itu cukup. Seminggu setelah mengirimkan esainya, Rika duduk bersama teman-temannya di ruang belajar.
Mereka sedang membahas tugas kelompok, tetapi pikiran Rika melayang. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Akhirnya, setelah beberapa menit, ia mengumpulkan keberanian dan berkata, “Aku ikut lomba menulis esai minggu lalu.” Semua mata langsung tertuju padanya.
“Serius? Itu keren banget, Rika!” kata Hana dengan mata berbinar.
“Wah, aku nggak tahu kamu suka nulis,” tambah Rain.
Rika merasa wajahnya memerah. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian, tetapi respons teman-temannya membuatnya merasa sedikit lebih percaya diri. “Aku nggak tahu hasilnya gimana, tapi… aku cuma mau coba,” katanya pelan.
“Itu udah langkah besar, Rika,” kata Hana sambil tersenyum. “Kita bangga sama kamu.” Kata-kata itu membuat hati Rika terasa hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa usahanya dihargai.
Malam itu, Rika duduk di kamarnya dengan senyuman kecil di wajahnya. Ia tidak tahu apakah ia akan memenangkan lomba itu atau tidak, tetapi itu tidak lagi penting. Yang penting adalah bahwa ia telah mencoba. Ia membuka jendela kecil di kamarnya dan memandang bintang-bintang di langit.
Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa dunia tidak terlalu gelap. Rika tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Ia tahu bahwa ia masih akan menghadapi banyak ketakutan dan keraguan. Tetapi malam itu, ia merasa bahwa ia telah mengambil langkah kecil menuju cahaya.
***
Langit sore itu berwarna jingga keemasan, seperti sebuah lukisan yang menenangkan hati. Rika duduk di bangku taman kampus, membiarkan angin lembut menyapu wajahnya. Ada sesuatu yang berbeda hari ini, sesuatu yang membuatnya merasa lebih ringan.
Beberapa minggu telah berlalu sejak ia mengirimkan esainya untuk lomba menulis. Ia tidak pernah benar-benar berharap untuk menang. Faktanya, ia bahkan tidak memeriksa pengumuman pemenang, karena baginya, keberanian untuk mencoba saja sudah lebih dari cukup. Tetapi Hana, dengan semangat khasnya, tidak membiarkan hal itu berlalu begitu saja.
“Rika, kamu nggak akan percaya ini!” Hana berkata dengan penuh antusias sambil berlari mendekatinya pagi itu.
Rika menatap Hana dengan bingung. “Ada apa?”
“Kamu jadi juara dua!” Hana menyerahkan selembar kertas pengumuman lomba kepadanya dengan mata berbinar.
Rika membacanya perlahan, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Namanya ada di sana, tertulis dengan jelas di urutan kedua. Hatinya berdebar kencang, bukan karena kebanggaan, tetapi karena rasa tidak percaya.
“Aku… menang?” tanya Rika dengan suara yang hampir berbisik.
“Iya! Aku udah bilang, kan? Kamu itu berbakat!” Hana memeluknya erat, dan Rika hanya bisa berdiri di sana, merasa seperti dalam mimpi.
Momen itu menjadi salah satu momen terbesar dalam hidupnya. Bukan karena penghargaan atau pengakuan, tetapi karena itu adalah pertama kalinya ia merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dirinya cukup.
Sejak saat itu, Rika mulai membuat perubahan kecil dalam hidupnya. Ia mulai berbicara lebih sering, meskipun masih dengan suara pelan. Ia mulai mencoba hal-hal baru, meskipun rasa takut masih sering menghantuinya.
Ia juga mulai menulis lebih banyak, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk berbagi dengan orang lain. Tulisan-tulisannya menjadi cara untuk mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam, sebuah jendela kecil yang ia buka untuk dunia luar.
Teman-temannya, terutama Hana, terus mendukungnya di setiap langkah. Mereka tidak pernah memaksanya untuk berubah, tetapi mereka selalu ada untuknya, memberikan dorongan ketika ia membutuhkannya. “Aku bangga sama kamu, Rika,” kata Hana suatu hari. “Kamu mungkin nggak menyadarinya, tapi kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan.”
Kata-kata itu selalu terngiang di kepala Rika. Ia tahu bahwa jalannya masih panjang, bahwa ia masih akan menghadapi banyak ketakutan dan keraguan. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia punya alasan untuk terus berjalan.
Sore itu di taman, Rika membuka buku catatannya dan mulai menulis. Ia menulis tentang dirinya, tentang perjalanannya, tentang rasa sakit dan luka yang pernah ia alami. Tetapi ia juga menulis tentang harapan—tentang bagaimana langkah-langkah kecil bisa membawa perubahan besar.
Ia menulis dengan senyuman kecil di wajahnya, sesuatu yang jarang ia tunjukkan. Dunia mungkin tidak berubah, tetapi ia merasa bahwa dirinya telah berubah, meskipun hanya sedikit. Saat matahari mulai tenggelam dibalik cakrawala, Rika menutup bukunya dan berdiri. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara segar memenuhi paru-parunya.
Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidup ini memiliki makna. Ia mungkin belum menemukan tujuan yang besar, tetapi ia tahu bahwa ia ingin terus mencoba, terus melangkah, dan terus mencari.
Dan itu sudah cukup. [*]